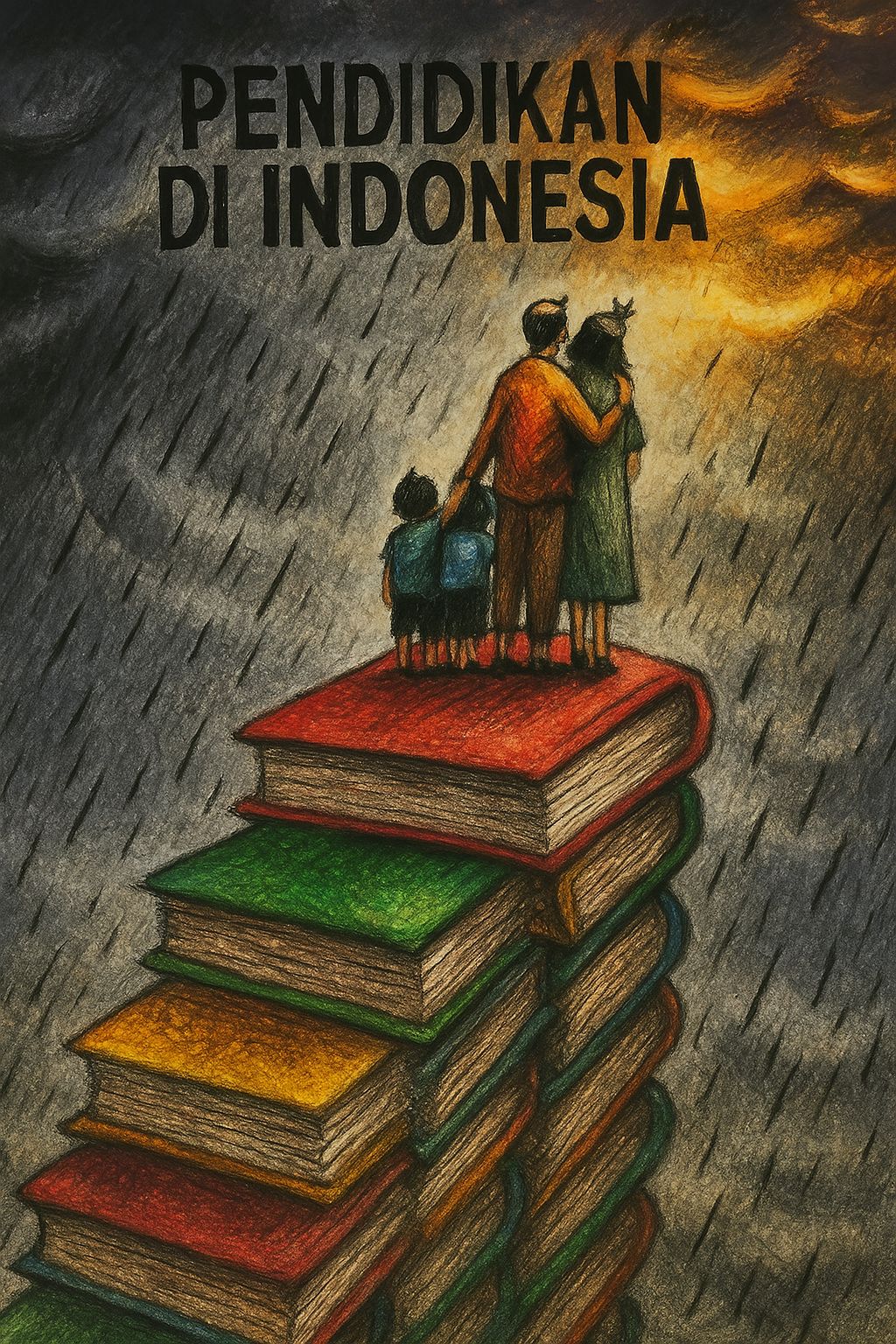“Jargon Indonesia Emas bukan hanya membutuhkan generasi muda yang ‘skillful’ dalam jumlah banyak, tapi juga ‘problem solver’ yang kaya empati.“
Saya baru saja berbincang dengan seorang ayah asal Finlandia. Rasa penasaran mendorong saya bertanya, “Mengapa negara ini selalu menduduki puncak peringkat Programme for International Student Assessment (PISA), sementara Indonesia masih berada di urutan bawah?”
Jawabannya bukan soal anggaran—Finlandia hanya menghabiskan €9.000 per siswa per tahun, lebih rendah dibandingkan Inggris yang €11.000 (data OECD 2024). Bukan pula jam belajar panjang; siswa Finlandia hanya menjalani 608 jam pelajaran setahun, jauh di bawah Indonesia yang mencapai 900 jam lebih.
Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan: mereka mengajarkan anak untuk bertanya, bukan sekadar menjawab.
Hari Pertama Sekolah: Kotak Misteri vs Upacara Bendera
Di Finlandia, hari pertama sekolah dasar (SD) tidak dimulai dengan membuka buku. Anak-anak diberi “kotak misteri” berisi benda-benda aneh: kunci berkarat, batu berlubang, atau foto pudar. Tugas mereka: buat 10 pertanyaan. Guru tidak mengoreksi benar-salah; yang dinilai adalah kedalaman pertanyaan.
Riset dari University of Helsinki (2024) menunjukkan, anak yang dilatih bertanya sejak usia 6 tahun memiliki kemampuan problem-solving 40% lebih tinggi saat remaja. Sebaliknya, di Indonesia, hari pertama SD sering diisi upacara bendera, hafalan Pancasila, dan daftar peraturan seragam. Pertanyaan pertama anak: “Boleh tanya, Bu?” Jawaban guru: “Nanti setelah pelajaran.”
Pendekatan Eropa: Filsafat untuk Anak Kecil
Di Belanda, anak TK sudah mengikuti sesi “Philosophy for Children” mingguan. Mereka duduk melingkar membahas topik seperti: “Apakah robot bisa punya teman?” Guru hanya memantik diskusi; siswa memimpin, tanpa jawaban benar—hanya argumen yang kuat.
Di Inggris, pertanyaan menjadi mata pelajaran wajib. Sejak Year 1 (usia 5–6 tahun), Philosophy for Children (P4C) diterapkan di 70% sekolah negeri (data DfE 2024). Anak-anak debat terstruktur, misalnya: “Should homework be banned?”
Di tingkat GCSE, mata pelajaran Critical Thinking mengajarkan untuk mendeteksi fake news dengan membandingkan headline BBC dan tabloid. Hasilnya? Siswa Inggris menduduki peringkat 3 di Eropa untuk evaluative reasoning (PISA 2022).
Pengalaman pribadi anak saya saat pindah ke Inggris pada 2017 semakin menguatkan hal ini. Di secondary school, tugas sejarah pertamanya bukan hafalan fakta seperti “Kapan Hitler mati?” atau “Kapan Perang Dunia II dimulai?” Melainkan: “Jika kamu hidup di Jerman 1933–1945, apa yang akan kamu rasakan?”
Seorang anak paling tidak harus bisa mempelajari fakta, seperti Nuremberg Laws, Kristallnacht, dan Holocaust (6 juta korban Yahudi, data Holocaust Memorial Museum). Kemudian, anak tersebut diajak untuk memilih perspektif personal seperti, sebagai anak Yahudi, pemuda Aryan, atau ibu rumah tangga biasa. Selanjutnya, anak tersebut menulis esai 1000 kata plus refleksi: “Bagaimana propaganda memengaruhi pilihanmu?”
Ini bagian dari “empathy history” dalam National Curriculum sejak 2014. Riset University College London (2023) menemukan, siswa yang belajar sejarah melalui perspektif personal memiliki empati sosial 28% lebih tinggi dan kemampuan argumen etis 35% lebih baik daripada yang hanya menghafal tanggal. Di Indonesia, sejarah sering sekadar daftar tahun: 1928, 1945, 1965—jarang ada ruang untuk bertanya, “Bagaimana rasanya jadi korban G30S?”
Data dan Dampak Nyata
Data World Economic Forum (2025) menyebutkan, 7 dari 10 negara dengan “future skills” terbaik adalah Eropa Utara dan Inggris—semua menerapkan play-based learning hingga usia 7 tahun. Di Indonesia, 60% kurikulum SD masih berbasis hafalan (Kemendikbudristek 2024). Akibatnya, siswa kita jago mengingat, tapi lemah merumuskan solusi.
Selama pandemi, siswa Finlandia menanam pohon dan mengukur polusi udara. Siswa Inggris membuat podcast tentang lockdown. Siswa Indonesia? Banyak yang bingung tanpa slide PowerPoint.
Di kelas Eropa, pertanyaan yang diberikan kepada murid adalah, “I wonder what would happen if…” Lalu, para siswa sontak langsung mencoba untuk menjawabnya tentu dengan pendapatnya pribadi, seperti dimulai dengan kalimat, “Let me try!”
Namun, jika kita melihat di Indonesia, guru hanya sebatas memberikan materi dan rumus lalu menyuruh siswa untuk mehafalkannya. Para siswa hanya menurut dan mengatakan, “Iya Bu/Pak”, saja.
Ironisnya, kita punya budaya gotong royong, tapi di sekolah, kolaborasi sering disamakan dengan menyontek. Di Swedia, ujian akhir dilakukan berkelompok. Di Inggris, Extended Project Qualification (EPQ) di tingkat A-Level mengharuskan proyek 5.000 kata dengan topik bebas (AI ethics atau sejarah K-pop) termasuk wawancara ahli dan presentasi panel. Nilai 50% berasal dari logbook refleksi harian.
Saya pernah bertanya pada istri kolega yang mengajar di Manchester, “Kalau jawaban anak salah terus lantas bagaimana?” Jawabnya: “Salah adalah data”. Kami akan menanyakan kepada siswa, “Apa yang kamu pelajari dari salahmu?” Sayangnya, di Indonesia, salah sering berarti malu, hukuman, atau bahkan dilabeli bodoh.
Anak Pinter Indonesia: Bukan Karena Sistem
Memang banyak anak Indonesia yang pintar dan sukses. Tapi mereka unggul bukan karena sistem pendidikan, melainkan kegigihan pribadi dan dukungan orang tua. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana mayoritas anak Indonesia—dari pelosok hingga kota besar—bisa secara rata-rata mengangkat (kualitas) peradaban bangsa.
Saya termasuk generasi 90an (lulus SMA tahun 1991). Banyak di antara kami sudah jadi “orang”. S2, S3, dosen, atasan perusahan dan pengusaha sukses. Jadi kurikulum dulu tidak gagal dong? Benar. Tapi ingat, merekalah yang sekarang duduk di pemerintah, DPR dan kementrian.
Dan sayangnya, kebijakan pendidikan gonta-ganti terus tiap menteri (Kurtilas → Merdeka → Lalu, apa lagi?). Selain itu, saat ini corruptive mindset makin menggila. Ditambah, 10 tahun terakhir, budaya permusuhan politik (pilpres, polarisasi) menular ke sekolah—guru takut bahas isu sensitif, anak belajar “benar = sesuai golongan”, seperti anak harus sekolah Islam sesuai pilihan orang tua. Jadi, sukses pribadi ≠ sukses sistem.
Generasi 90an bisa naik karena kompetisi masih rendah, populasi bonus demografi, dan ekonomi tumbuh. Tapi mereka gagal membangun sistem yang adil untuk anak-anak sekarang.
Barat vs Timur: Mana Role Model yang Tepat?
Lima tahun terakhir memang mengguncang. Terdapat polarisasi politik di AS/UK seperti adanya Brexit, Jan 6, dan campus protest. Ada pula krisis identitas Eropa (imigrasi, populisme, nilai “woke” vs tradisi). Namun, di kutub lain terdapat Tiongkok yang tampak solid dengan pertumbuhan ekonomi-nya sebesar +7%, teknologi (EV, AI), proyek Belt & Road di 150 negara.
Finlandia (dan Eropa Utara) punya budaya kebebasan berpikir, kemandirian, dan rendahnya hierarki yang sudah ratusan tahun terbentuk. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Masih kuat budaya guru sebagai “raja kelas”, orang tua yang takut anak “terlalu banyak bertanya”, dan masyarakat yang lebih menghargai nilai 100 daripada proses.
Jadi, meniru 100% Finlandia = latah. Tapi menolak total ide “bertanya” karena “bukan budaya kita” = tanggung. Kita bisa ambil esensinya: bukan “kotak misteri” atau “play-based sampai umur 7”, tapi latih anak bertanya dan berpikir kritis dalam konteks kita.
Cina dan Korea: Bukan Hanya Hafalan
Di konteks China dan Korea, mereka melaksanakan ujian dengan sangat ketat (gaokao, suneung), yang mana mirip seperti UN/SNBT kita. Jam belajar mereka juga panjang, mirip seperti les tambahan sampai malam. Mereka sangat menargetkan untuk mendapat Nilai A, mirip seperti ekspektasi orang tua pada umumnya di Indonesia.
Tapi ini cuma separuh cerita. Apa yang bikin Cina/Korea unggul meski hafalan?
Bukan hafalannya. Tapi budaya malu gagal + masyarakat yang menghargai proses belajar. Berikut ilustrasi sederhananya:
| Aspek | Cina/Korea | Indonesia |
| Mencontek | Aib keluarga | “Bantu Teman” |
| Belajar di KRL | Biasa | “Cie, sok rajin” |
| Ujian Nasional | Penerbangan dihentikan | Jalanan macet, klakson |
| Orang Tua | Investasi les = investasi masa depan | Les = biar tidak ketinggalan, tapi nilai turun = malu |
| Masyarakat | “Anak ini rajin” = pujian | “Anak ini rajin” = ejekan |
Jadi, bukan sistem ujiannya yang bikin mereka maju. Tapi budaya di belakangnya. Kalau kita cuma tiru ujian ketat + hafalan, tanpa tiru budaya malu gagal + hormati proses, kita tetap versi murah dari Cina/Korea.
Apakah “Barat Runtuh”? Tidak. Tapi sedang “Remodelling”. Mari kita simak tabel di bawah ini:
| Indikator | Barat (AS/UK/Eropa) | Cina |
| Inovasi (paten per kapita) | AS: 1.800 paten/milion penduduk (WIPO 2024) | Cina: 1.100 (tapi 70% paten “utility model” = kecil) |
| Nobel Sains (2000–2024) | 180 pemenang | 3 pemenang |
| Unicorn startup | 600+ (Silicon Valley, London) | 200+ (tapi 80% didanai negara) |
| Kebebasan riset | Tinggi (kampus bebas kritik pemerintah) | Rendah (AI facial recognition = state tool) |
Barat tidak runtuh. Mereka sedang berantem internal—seperti remaja puber. Itu tanda kesehatan demokrasi: nilai diuji, direvisi, diperbaiki. Bagaimana dengan China? Mereka tampak solid karena tidak boleh berantem di depan umum. Sebagai pengingat, China pernah mengalami era Great Leap Forward 1958–1962 yang menyebabkan 30 juta orang mati kelaparan. Namun peristiwa tersebut tidak boleh dibahas di sekolah.
Saya akan berikan tabel tentang bagaimana “Kekuatan dan Kelemahan Tersembunyi dari Pendidikan di China:
| Kekuatan | Kelemahan |
| Displin & skala: 300 juta siswa, ujian gaokao = meritokrasi ketat. | Kreativitas rendah: PISA 2022 Creative Thinking: Cina rank 38, Finlandia 5. |
| STEM fokus: 40% lulusan sarjana teknik (vs AS 6%). | Copy-paste culture: 60% paten Cina = modifikasi, bukan orisinal (Nature 2023). |
Cina unggul di “manufacturing superpower”. Tapi kalah di “innovation superpower”.
Sebagai contoh:
- TikTok? Algoritma dari ByteDance—tapi ide “short video” dari Vine (AS).
- Huawei 5G? Paten inti dari Qualcomm (AS).
- EV battery? BYD unggul—tapi lithium refinement dari Australia & Chile.
Pendidikan Cina = pabrik tenaga kerja terampil dalam jumlah yang masif
Pendidikan Barat = pabrik ide gila yang kadang gagal, tapi kadang ubah dunia.
Budaya & Peradaban: Bukan Hanya Tugas Pemimpin
Persoalan mendasar di Indonesia adalah budaya dan peradaban. Dan perubahan itu memang butuh gerakan masal. Tapi pertanyaannya: harus menunggu pemimpin dulu?Pemimpin dan elit politik kita? Ya, banyak yang “begitu”. Korup, pragmatis, sibuk rebutan kursi. Kalau kita tunggu mereka, kita bisa menunggu sampai cucu kita punya cucu.
Mulai dari Mana?
Saya bukan ahli pendidikan, hanya seorang ayah beranak 4 beristri satu, yang telah memutuskan agar anak-anak saya untuk belajar bukan dengan kurikulum Indonesia, dengan menjadi diaspora hampir 20 tahun di tiga negara.
Saya mengerti rasanya pesimis. Saya juga hidup di sistem ini. Tapi justru karena itu, saya pilih tidak menyerah pada sinisme. Kita tidak butuh revolusi. Kita butuh ribuan percobaan kecil, oleh orang-orang biasa, yang saling menguatkan. Sejarah membuktikan: perubahan peradaban besar selalu dimulai dari bawah—oleh orang biasa yang muak, tapi memilih bertindak kecil tapi konsisten.
Di Finlandia? Bukan presiden yang mulai. Guru-guru desa di tahun 1970-an yang muak dengan hafalan, lalu bereksperimen di kelas masing-masing. Baru 20 tahun kemudian, pemerintah ikut. Di Inggris dengan P4C? Dimulai oleh sekelompok filsuf dan guru di universitas kecil tahun 1970-an. Mereka latih guru sukarelawan. Baru 2002 masuk kurikulum nasional.
Solusi sederhana, tapi kolektifnya adalah: Di rumah: Ganti “Sudah makan?” menjadi “Hari ini kamu bertanya apa di sekolah?” Di sekolah: Kurangi multiple choice; tambah proyek seperti wawancara tetangga soal banjir, lalu tulis refleksi. Di masyarakat: Normalisasi “Saya belum tahu, mari cari tahu bareng.”
Kita tidak perlu China versi murah atau Barat versi miskin. Kita butuh “Indonesia Hybrid”. 10 tahun lagi, kita tidak tiru siapa-siapa. Kita jadi role model baru. Bisa dimulai dari yang paling kecil sekarang juga: bukan “Apa jawabannya?” melainkan “Apa pertanyaannya?”
Oleh: Ruly Achdiat (20 tahun Diaspora Singapura, London dan Dubai, Chief Architect, Department Economics and Tourism, Government of Dubai)
Pemikiran dan Refleksi Diaspora Nahdlatul Ulama (PR Di NU) merupakan ruang bagi gagasan, refleksi, dan kontribusi intelektual dari diaspora Nahdliyyin. Platform ini menyatukan wawasan yang berakar pada keahlian masing-masing para diaspora NU yang menawarkan perspektif tentang Islam yang berlandaskan Indonesia sebagai masyarakat yang dinamis, dan tentang nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang tetap relevan di dunia saat ini. Fokus “PR Di NU” adalah isu-isu mendesak abad ke-21, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM). Tema-tema seperti etika Islam dalam kecerdasan buatan, keberlanjutan lingkungan, kesehatan digital, energi, dan transformasi sosial berfungsi sebagai gerbang untuk memperkaya percakapan global melalui lensa Ahlussunnah wal Jama’ah. (Editor Utama: Efri Arsyad Rizal)